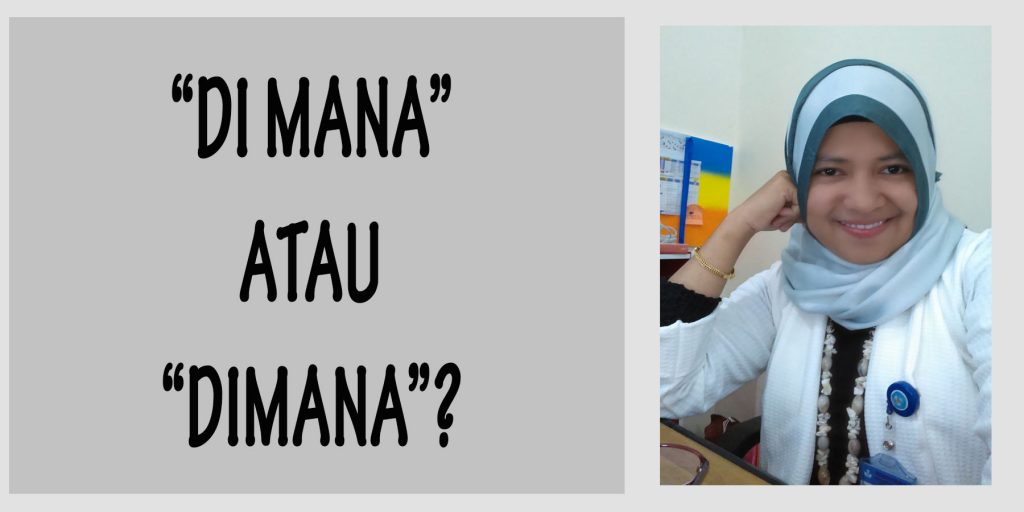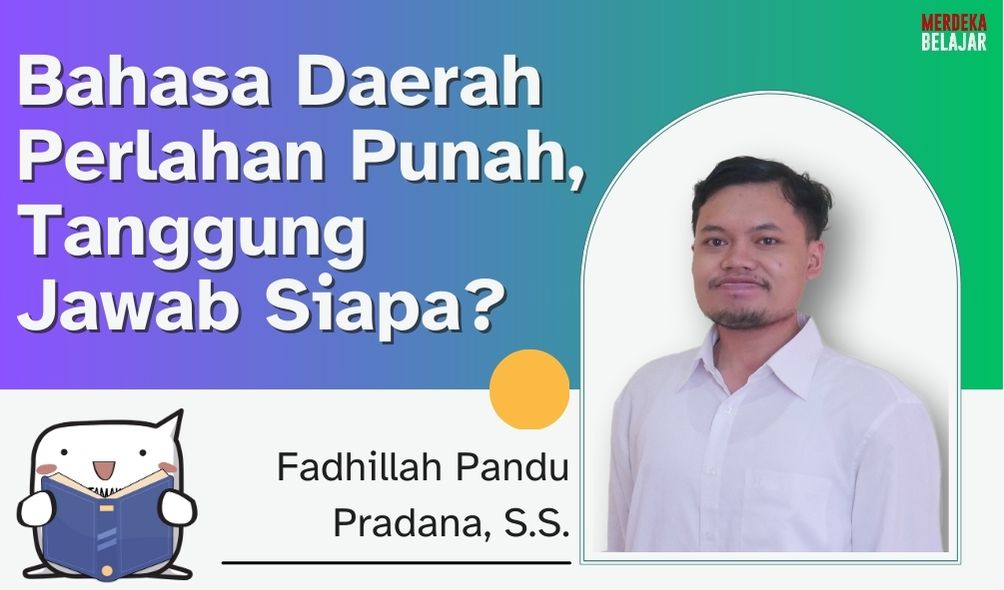Glenn Christison Manusama dan Sheila Imanuella Thenu
Duta Bahasa Provinsi Maluku Tahun 2025
Semua guru adalah kriminal. Semua guru adalah pengkhianat. Jika mengikuti apa kata hukum, semua guru adalah narapidana. Namun, jika dilihat lagi, semua guru juga adalah korban. Benarkah? Menurut UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Ketentuan ini dielaborasi lebih lanjut dalam Perpres No. 63 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa bahasa daerah dapat menjadi bahasa pengantar, tetapi hanya pada tahun pertama dan tahun kedua di sekolah dasar. Artinya, hampir semua Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) wajib menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun begitu, guru-guru yang kerap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sering kali hanya guru-guru bahasa Indonesia. Jika hukum sudah sejelas ini, mengapa penggunaan bahasa di ruang kelas terkesan masih dilakukan seenaknya?

Kewajiban ini muncul sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga muruah bahasa Indonesia agar diutamakan dalam ruang pendidikan. Mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia selalu menjadi mata pelajaran wajib yang diberikan kepada setiap pelajar. Ini menjadikannya sangat penting dalam rangka mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, sebuah visi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Visi ini hadir untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Salah satu unsur penting pendidikan bermutu adalah tenaga pendidik yang kompeten. Namun, kompetensi tenaga pendidik khususnya dalam hal berbahasa Indonesia yang baik dan benar masih jauh dari kata sempurna.
Menurut Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2024, 73,5% guru dan 47,8% dosen yang mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif perlu ditingkatkan kemahiran berbahasanya. UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Keterbatasan tenaga pendidik di Indonesia dalam berbahasa Indonesia sangat disayangkan karena peran tenaga pendidik untuk menjadi teladan di depan para pelajar. Sementara itu, 53,9% pelajar SMP dan 50,5% pelajar SMA belum memenuhi standar kemahiran berbahasa. Cukup mengkhawatirkan, kan? Padahal, pelajar adalah garda terdepan generasi muda dalam menormalisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Di sisi lain, jika kita bandingkan rata-rata tingkat kemahiran berbahasa di Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia timur berada pada posisi yang rendah. Sebut saja, empat peringkat terbawah ditempati oleh Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Sementara itu, wilayah dengan capaian tingkat kemahiran tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan kita khususnya di wilayah bagian timur Indonesia masih memiliki PR besar dalam hal kemampuan dan kemahiran berbahasa. Di Provinsi Maluku, skor rata-rata kemahiran berbahasa Indonesia ialah 402 dengan peringkat marginal. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Data ini bukan hanya memperlihatkan rendahnya pengutamaan bahasa Indonesia secara umum, melainkan adanya ketimpangan tingkat kemahiran berbahasa antarprovinsi yang masih menjadi tantangan serius.
Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus memartabatkan bahasa Indonesia dalam skala nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah melalui pencetusan Trigatra Bangun Bahasa, sebuah rumusan untuk membangun kesadaran berbahasa. Trigatra Bangun Bahasa terdiri atas tiga aspek, yakni pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Trigatra Bangun Bahasa juga telah digunakan sebagai moto oleh Duta Bahasa, representasi generasi muda dalam hal pembinaan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.
Meskipun begitu, apakah semua ini cukup? Terlepas dari segala upaya pemerintah, jawabannya ialah tidak. Bahasa Indonesia berdaulat masih belum sepenuhnya benar, terutama di ranah pendidikan. Kami menemukan empat faktor yang menghalangi kedaulatan bahasa Indonesia di ruang kelas. Pertama, kompetensi tenaga pendidik dalam hal berbahasa Indonesia yang belum memadai. Kedua, xenomania bahasa asing. Ketiga, normalisasi berbahasa daerah di ruang kelas. Keempat, bahasa Indonesia yang diremehkan, dibuktikan oleh lemahnya penegakan kualifikasi akademik pengajar bahasa Indonesia.
a. Kompetensi Tenaga Pendidik yang Belum Memadai
Bahasa merupakan alat utama untuk bernalar. Melalui bahasa, tenaga pendidik melatih pelajar untuk menulis, membaca, mendengar, dan berbicara secara kritis. Proses berpikir yang logis, kritis, dan sistematis bergantung pada penguasaan bahasa seseorang. Maka, prasyarat kompetensi yang memadai adalah kemampuan berbahasa yang baik dan benar. ‘Baik’ berarti mampu memosisikan bahasa sesuai dengan situasi, sedangkan ‘benar’ berarti sesuai dengan kaidah.
Faktanya, pengajaran bahasa Indonesia, termasuk hal-hal mengenai kaidah itu membosankan. Setidaknya itu yang dipercaya banyak pelajar. Benarkah masalahnya ada di bahasa kita sendiri atau pada cara bahasa Indonesia diajarkan? Siapa di sini yang jenuh ketika harus menganalisis struktur kalimat, menghafal aturan penggunaan tanda baca, atau membaca teks panjang tanpa henti? Itulah kenangan sebagian besar pelajar saat berhadapan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita sering dihadapkan pada hafalan kaidah tata bahasa, analisis struktur kalimat, atau membaca teks panjang yang monoton. Akibatnya, mata pelajaran yang seharusnya membangun kecintaan pada Indonesia malah seolah menjadi momok yang dihindari pelajar.
Persoalan utama bukan terletak pada bahasa Indonesia itu sendiri. Masalahnya lebih sering muncul karena keterbatasan kompetensi tenaga pendidik. Banyak guru bahasa Indonesia memang menguasai materi, tetapi kurang mampu menghidupkan kelas dengan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif. Pelajaran bahasa akhirnya terjebak dalam ceramah panjang, latihan soal, dan hafalan. Akibatnya, motivasi belajar siswa menurun. Siswa tidak melihat bahasa Indonesia sebagai keterampilan penting (Baharudin dkk, 2024). Padahal, inilah fungsi utama bahasa menjadi sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien.
Kompetensi tenaga pendidik yang tidak memadai dalam berbahasa Indonesia juga berdampak pada peserta didik. Sebagai teladan, tenaga pendidik harus mampu menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik agar dapat menghasilkan kemampuan yang memuaskan. Bahasa Indonesia bukan hanya bermanfaat bagi peserta didik, melainkan juga bagi tenaga pendidik yang wajib mengajar dengan jelas dan mudah dipahami. Bayangkan jika seorang tenaga pendidik tidak menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten, hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya penanaman rasa bangga dan cinta peserta didik terhadap bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional.
b. Xenomania Bahasa Asing
Sudah berapa kali kamu mendengar kata slide, online, dan deadline di sekolah atau di kampus? Pastinya sudah lebih dari yang bisa dihitung dengan jari, kan? Pernahkah kamu mendengar kata papan tombol, gawai, dan perambansaat sedang duduk di ruang kelas? Prevalensi penggunaan bahasa asing di lingkungan sekolah atau kampus tidak bisa disangkal, baik dosen saat sedang menyajikan materi, mahasiswa saat sedang bertanya, maupun siswa saat sedang presentasi, semua orang seolah-olah berlomba untuk menggunakan istilah bahasa asing dalam berkomunikasi.
Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan bahasa asing pada ranah pendidikan adalah globalisasi yang memudahkan pembelajaran budaya serta bahasa asing. Namun, terlepas dari itu, dalam perspektif banyak orang, bahasa asing khususnya bahasa Inggris sering dijadikan simbol gengsi dan intelektualitas. Paradigma yang makin marak di tengah masyarakat bahwa kemampuan berbahasa asing menunjukkan kepiawaian dan kompetensi. Sebaliknya, penggunaan bahasa Indonesia dipandang sebagai sesuatu yang sederhana dan biasa saja. Hasilnya, siswa dan mahasiswa selalu mencoba untuk menormalisasikan penggunaan istilah asing.
Fenomena ini bukan sekadar soal pilihan kata, melainkan juga soal struktur kalimat. Bahasa asing, seperti bahasa Inggris memiliki struktur kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ketika kosakata dan struktur bahasa Inggris dipaksakan ke dalam bahasa Indonesia, hasilnya sering keliru. Misalnya, pada penggunaan frasa yang tidak tepat, seperti penggunaan kata di mana dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan sebagai pengganti kata where dalam bahasa Inggris. Contoh lain yang sering kali terjadi adalah kesulitan membedakan penggunaan kata kami dan kita yang dalam bahasa Inggris berarti us/we tanpa ada perbedaan makna leksikal. Kalimat kompleks yang diterjemahkan mentah-mentah akan menghasilkan bahasa Indonesia yang kaku dan tidak alami. Akibatnya, siswa kesulitan membedakan struktur kalimat bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang tidak baku yang berasal dari hasil terjemahan langsung bahasa asing.
c. Normalisasi Berbahasa Daerah
Kenyataan yang terjadi di Indonesia terkhusus di wilayah Indonesia timur menunjukkan bahwa sebagian besar guru lebih memilih menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Berdasarkan pengalaman kami, di Provinsi Maluku, guru-guru lebih sering mengajar menggunakan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar KBM bahkan terjadi setelah tahun pertama dan kedua di jenjang SD. Artinya, selain terancam oleh xenomania bahasa asing, bahasa Indonesia di ranah pendidikan juga harus mempertahankan kedudukannya dari normalisasi penggunaan bahasa daerah. Meskipun banyak yang berlindung di balik frasa melestarikan bahasa daerah, normalisasi penggunaan bahasa daerah di dunia pendidikan sebagai bahasa pengantar bukanlah ide yang tepat. Mengapa demikian? Bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah dua hal yang berbeda. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa daerah. Normalisasi atau pembiasaan penggunaan bahasa daerah secara terus berdampak pada tingkat pemahaman peserta didik pada bahasa Indonesia. Hal ini juga akan berpengaruh pada kecakapan literasi peserta didik dan tentunya menyulitkan pemahaman peserta ketika berhadapan dengan buku-buku teks dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan siswa akan penjelasan guru yang sudah disederhanakan. Padahal, buku teks yang disediakan dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari kembali materi.
d. Bahasa Indonesia yang Diremehkan di Negeri Sendiri
Di Indonesia, tidak sedikit tenaga pendidik yang mengajar bahasa Indonesia tanpa memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang bahasa. Awaluddin Tjalla, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud mengungkapkan bahwa 3 dari 10 guru di Indonesia mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang studinya, termasuk guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Fenomena ini mengungkapkan satu hal, bahasa Indonesia dianggap remeh, seolah-olah siapa pun bisa mengajarkannya hanya karena telah memakainya dalam kehidupan sehari-hari.
Pandangan seperti ini berbahaya. Menguasai bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari tidak sama dengan memahami bahasa Indonesia dengan segala kaidah dan aturan bahasa yang dimiliki. Seorang guru yang tidak memiliki dasar linguistik atau pedagogi bahasa akan cenderung hanya mengajarkan bahasa Indonesia tanpa pemahaman mengenai kompleksitas bahasa Indonesia itu sendiri. Akibatnya, siswa mungkin bisa berbicara, tetapi kurang terlatih untuk berpikir, menalar, dan menulis secara runtut dan bermakna.
Kondisi ini juga membawa dampak kultural. Jika siapa pun dianggap bisa mengajar bahasa Indonesia, pesan yang disampaikan ke masyarakat luas adalah bahwa bahasa Indonesia tidak membutuhkan keahlian khusus. Bandingkan dengan mata pelajaran lain, mustahil seorang lulusan ekonomi diminta mengajar fisika. Namun, untuk bahasa Indonesia, situasi ini dianggap wajar. Dari sini, terlihat jelas bahwa posisi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan masih dianggap sekadar pelengkap, bukan ilmu yang bermartabat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bahasa Indonesia akan semakin terpinggirkan di tanah airnya sendiri. Maka, perlu ada kebijakan yang lebih tegas. Pengajaran bahasa Indonesia harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar memiliki latar belakang pendidikan bahasa. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kualitas pembelajaran, tetapi juga mengangkat martabat bahasa Indonesia sejajar dengan disiplin ilmu lainnya.
Masalah ini bukan hanya menyangkut pemartabatan bahasa Indonesia, melainkan juga berimplikasi langsung pada mutu pendidikan nasional. Sebagai bahasa pengantar dalam ruang pendidikan, lemahnya pemartabatan bahasa Indonesia berarti lemahnya mutu pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam data PISA tahun 2023, yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 68 dari 81 negara yang diteliti. Kualitas pendidikan di Indonesia sendiri tidak mungkin terlepas dari kualitas bahasa pengantarnya. Permasalahan ini adalah salah satu dari banyaknya faktor yang menghambat terciptanya pendidikan bermutu di Indonesia. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jantung dari proses berpikir, bernalar, dan memahami ilmu pengetahuan. Apabila bahasa yang digunakan dalam pendidikan lemah, proses berpikir kritis generasi muda pun akan rapuh.
Di titik inilah, kedaulatan bahasa Indonesia menjadi mutlak. Bahasa Indonesia bukan hanya simbol identitas nasional, melainkan juga fondasi yang menopang sistem pendidikan. Tanpa pengutamaan bahasa Indonesia, visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” hanya akan menjadi slogan kosong. Kita perlu memastikan bahwa setiap tenaga pendidik tidak hanya memahami materi ajar, tetapi juga memiliki kecakapan berbahasa yang mumpuni.
Selama ini, peningkatan kompetensi guru jarang difokuskan pada bidang bahasa. Padahal, peningkatan kompetensi guru dalam berbahasa Indonesia merupakan solusi strategis untuk menciptakan pendidikan bermutu. Guru yang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik tidak hanya memperjelas penyampaian materi, tetapi juga menjadi anutan berbahasa bagi siswa. Ini akan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, mengurangi kesenjangan kemahiran antarwilayah, serta membuat proses KBM lebih interaktif dan inklusif. Selanjutnya, kompetensi tenaga pendidik dapat diukur dan dijamin melalui instrumen seperti UKBI.
Pada akhirnya, kedaulatan bahasa Indonesia berbanding lurus dengan terwujudnya pendidikan bermutu hebat. Jika kita gagal memartabatkan bahasa Indonesia di ruang kelas, kita juga mempertaruhkan mutu pendidikan bangsa. Kita harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa kebanggaan yang menarik untuk dipelajari. Dengan demikian, kita dapat menapaki jalan menuju bangsa yang cerdas, bermartabat, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, mari, kita tegakkan kedaulatan bahasa Indonesia—tidak hanya demi identitas, tetapi juga demi masa depan pendidikan yang bermutu hebat bagi seluruh anak bangsa.
Referensi
- https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/12866-partisipasi-semesta-wujudkan-pendidikan-bermutu-untuk-semua-
- https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8KyX8BEk-30-guru-mengajar-tak-sesuai-latar-belakang-pendidikan
- (PDF) Pembelajaran interaktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar