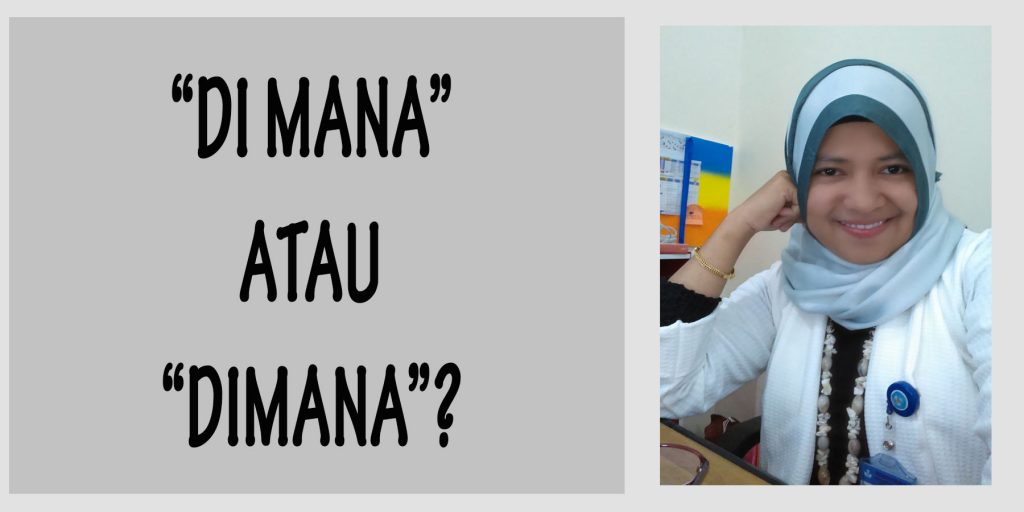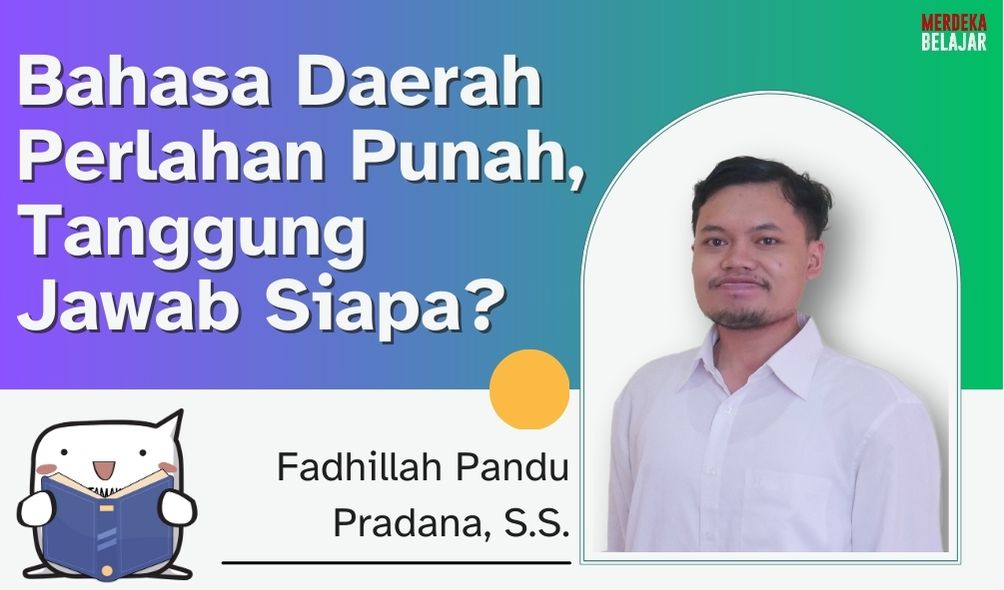Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.
Penerjemah Ahli Muda di Balai Bahasa Provinsi Maluku
Pada tahun 1999, Maluku mengalami tragedi kemanusiaan yang tercatat sebagai konflik terbesar di Indonesia. Konflik yang yang tidak hanya meninggalkan trauma bagi orang Maluku, tetapi juga meretakkan salah satu pilar terkuat kebudayaan Maluku: pela-gandong. Pela-gandong adalah sebuah ikatan persaudaraan yang dibangun ratusan tahun bukan hanya antaragama, melainkan juga antaretnis. Ini adalah budaya yang memelihara keharmonisan masyarakat Maluku. Konflik Maluku juga meninggalkan luka kolektif yang akhirnya memetakan beberapa wilayah di Maluku, khususnya di Kota Ambon, berdasarkan agama. Selain itu, konflik kemanusiaan ini makin mempertegas stigma masyarakat Indonesia terhadap karakter orang Maluku yang ekspresif, keras kepala, gampang naik pitam, dan gampang terbakar isu, bahkan hanya isu kecil, walaupun sebenarnya stigma ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua orang Maluku. Tidak dapat dimungkiri bahwa konflik Maluku memang didasari oleh bahasa dalam bentuk kabar bohong, ujaran provokatif, dan politik identitas yang akhirnya berujung pada kekerasan yang menyeret semua lapisan masyarakat Maluku.

Setelah 26 tahun berlalu, wajah Maluku justru menampilkan paradoks. Bulan September 2025, saat terjadi megademonstrasi mengenai penolakan kebijakan DPR yang berlangsung ricuh bahkan berakhir anarkistis, Maluku, terkhusus Ambon, tampil dengan wajah yang berbeda. Saat terjadi kebakaran dan penjarahan di daerah-daerah demonstrasi, mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat Ambon menggelar demonstrasi yang berjalan lancar dan damai. Orang Maluku juga turut menyuarakan protes secara lantang, tetapi tetap tertib. Mereka bahkan menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai dan disertai permintaan maaf kepada warga kota yang aktivitasnya terganggu, seperti arahan koordinator lapangan di awal pengumpulan massa. Dia menyampaikan, ”Gerakan ini gerakan damai. Slogan beta rasa ale rasa harus dijunjung tinggi dalam bentuk lisan dan perbuatan.” Selain itu, salah satu spanduk yang mereka bawa pun bertuliskan, ”Tegakkan Keadilan dan Dengarkan Suara Rakyat, Jaga Persatuan, Gotong royong Rawat Demokrasi.” Saat melakukan orasi di depan Markas Polda Maluku pun orator masih menyuarakan kalimat damai, ”Di sini tidak ada anarkis. Kita ada untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.” Masyarakat yang telah dicap dengan sifat sumbu pendek justru menampilkan kedewasaan demokrasi. Bagaimana karakter orang Maluku yang terkenal keras, ekpresif, cepat tersulut isu, cepat naik pitam, dan sumbu pendek dapat dengan damai menjalankan demonstrasi saat semua daerah di Indonesia yang melakukan demoberujung anarkistis? Apakah orang Ambon tidak berwatak keras lagi? Apakah orang Ambon sudah tidak ekspresif? Apakah orang Ambon tidak ricuh lagi? Ini adalah fenomena yang menarik untuk dikaji.
Faktanya, orang Maluku masih berwatak keras, orang Maluku masih ekspresif, dan kericuhan masih saja ada di Maluku, terkhusus di Kota Ambon. Namun, ada yang membuat orang Maluku, orang Ambon, tampil dengan wajah berbeda pada tahun 2025. Hal tersebut ialah peran bahasa. Tanpa orang Maluku sadari bahasa jugalah yang memainkan peran sentral dalam perubahan ini. Jika pada tahun 1999 bahasa adalah pemantik konflik, tahun 2025 bahasa adalah peredam konflik. Setiap kericuhan yang terjadi di Maluku, orang Maluku akan menstimulasi diri mereka dengan kalimat, “Katong seng mau dapa bodo lai.”
Oleh karena itu, demonstrasi pada 1 September 2025 bahasa bukan lagi pemicu konflik, melainkan instrumen pengendali amarah, media transformasi, dan pengikat solidaritas. Peran bahasa tidak sesederhana yang dikenal orang, yakni sebagai alat komunikasi saja, tetapi lebih dari itu, bahasa memiliki peran yang sangat kompleks. Peran itu di antaranya adalah sebagai berikut.
- Bahasa sebagai pengendali amarah. J. C. Alexander (2024) menjelaskan konsep trauma kultural dalam bukunya Cultural Trauma and Collective Identity, yaitu bahwa luka kolektif tidak hanya melahirkan trauma dan menandainya selamanya dalam pikiran mereka, tetapi juga dapat melahirkan identitas baru yang dibangun dengan kesadaran baru. Orang Maluku sadar bahwa konflik 1999 telah merobek kain putih pela-gandong yang dipicu dari tuturan yang hanya mengekspresikan kemarahan. Hal ini menjadi trauma yang sulit dihilangkan dari pikiran mereka karena berujung pada kekerasan, tetapi juga membantu mereka melahirkan identitas baru dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, dalam demo baru-baru ini, bahasa tidak lagi disampaikan secara membabi buta, tetapi dipilih dengan kesadaran untuk menciptakan sebuah identitas baru bagi orang Maluku, seperti yang terlihat dalam sebuah unggahan media sosial, ”Mau bilang buat mahasiswa di Ambon! Ingat, katong punya aspirasi sama tapi katong pung sejarah kota yang berbeda dari tempat lain”. ”… di Ambon nih fasilitas umum dibuat dari APBD yang saki-saki, jadi jang rusak akang lai.” Kalimat itu merujuk pada konflik ’99 yang dapat mengingatkan masyarakat Maluku tentang sakitnya dampak tragedi kemanusiaan 1999. Selain itu, frasa dibuat dari APBD yang saki-saki merujuk pada sebuah perjuangan yang telah mengorbankan banyak hal, baik material maupun nonmaterial. Pada poin ini, secara tidak langsung pembuat akun telah memfungsikan bahasa sebagai rem sosial yang mengendalikan emosi kolektif, bukan ekspresi kemarahan.
- Bahasa sebagai tindakan politik. John L. Austin (1962) dalam teori tindak tuturnya menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan (speech act). Para orator di Kota Ambon menyadari bahwa orasi mereka bukan hanya bentuk ekspresi kemarahan, melainkan tindakan politik yang menegaskan aspirasi rakyat karena kepentingan yang diperjuangkan tidak hanya milik kelompok tertentu, tetapi milik kepentingan bersama sebagai saudara. Bukan hanya orator demonstrasi, masyarakat juga melalui tulisan mereka di media sosial sebelum tanggal 1 September 2025, seperti ”Jadi, hindari anarkisme, jangan merusak fasilitas umum, apalagi menjarah orang rumah. Sama sekali tidak bawa untung buat warga Ambon. Tunjukkan protes damai seperti apa” mengingatkan para demonstran tentang tujuan utama demonstrasi, yakni untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga menyadarkan para demonstran bahwa tindakan anarkistis tidak memberi keuntungan apa pun kepada warga Ambon.
Bahasa sebagai media transformasi konflik. Johan Galtung (1996) dalam bukunya Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization menegaskan bahwa konflik tidak harus dihapus, tetapi bisa ditransformasikan menjadi interaksi konstruktif. Demonstrasi di Ambon adalah bukti transformasi itu. Ekspresi kemarahan masyarakat yang dulunya tersalur dalam bentuk kekerasan tertransformasi ke jalur ujaran politik. Seruan kolektif, nyanyian protes, dan pidato orator, serta saran damai, seperti ”Kalo ada mahasiswa atau massa aksi yang picu anarki, berarti dia seng sayang Ambon” dalam sebuah unggahan di media sosial telah menjadi bentuk sublimasi emosi. - Bahasa sebagai wajah kolektif. Brown & Levinson (1987) dalam bukunya Politeness: Some Universals in Language Usage menekankan pentingnya menjaga wajah sosial atau face. Orang Maluku menyadari bahwa citra sumbu pendek, cepat naik pitam, kakarasang melekat lebih kuat pascakonflik ’99. Demonstrasi pada 1 September 2025 yang penuh dengan bahasa damai dan ujaran yang terukur menjadikannya sarana yang tepat untuk pembuktian bahwa Maluku mampu menampilkan wajah demokrasi yang dewasa di mata Indonesia. Hal ini bahkan terlihat pada unggahan yang muncul sebelum tanggal 1 September 2025 yang bertuliskan, ”Dan untuk bapa-ibu penjabat di Ambon, massa sebanyak apa pun, keluar saja kasi tunju muka, lah coba dialog, lalu sampaikan aspirasi masyarakat ke pusat sana. Tunjukkan kalo di Ambon katong beda.” Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Maluku ingin memberikan citra Maluku yang berbeda di mata Indonesia dan dunia.
Peran-peran bahasa yang kompleks inilah yang mengubah kelemahan orang Maluku pada tahun 1999 memecah persatuan sekarang menjadi kekuatan demokrasi. Orang Maluku tetap lantang dan penuh energi, tetapi energi itu diarahkan melalui ujaran damai, dipandu oleh kesadaran akan trauma konflik 1999, dan diperkokoh nilai pela-gandong. Pengalaman inilah yang melahirkan kedewasaan demokrasi kemampuan mengelolah konflik melalui bahasa dan budaya, bukan kekerasan. Semoga kedewasaan demokrasi yang ditampilkan orang Maluku menjadi pelajaran berharga bagi semua rakyat Indonesia yang ber-Pancasila.