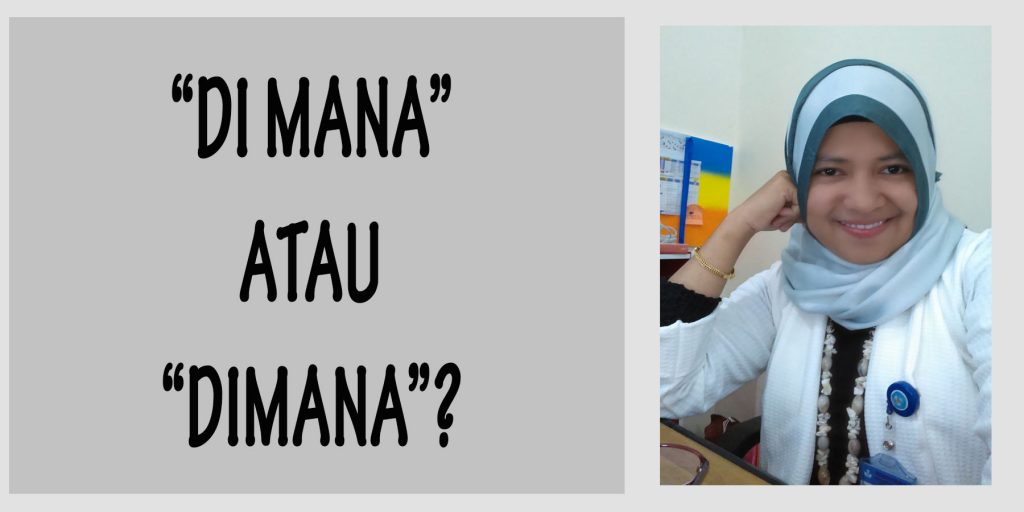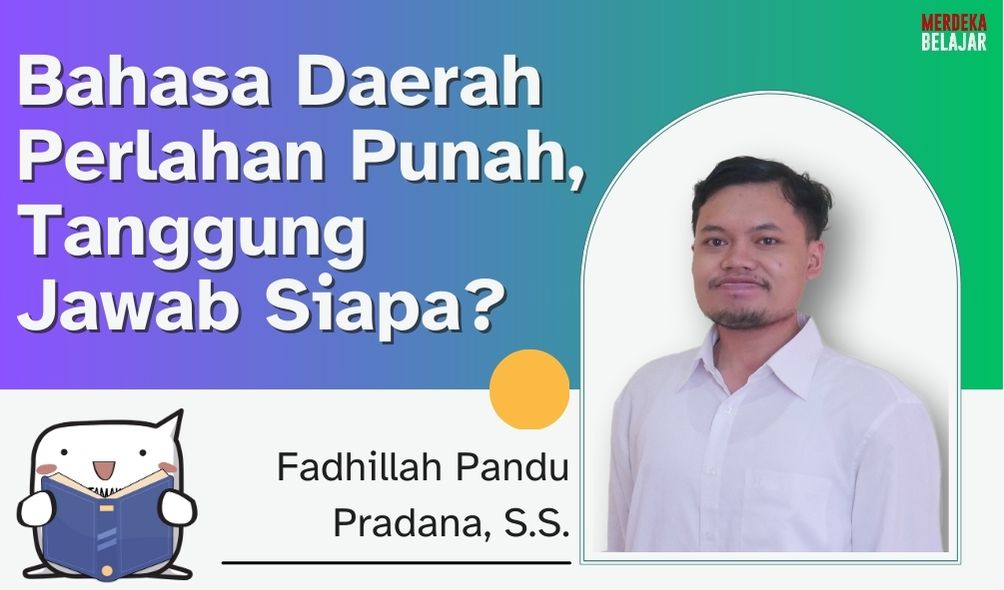Faradika Darman, S.S., M.A.
Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Maluku
Revitalisasi bahasa daerah merupakan upaya strategis dan sistematis dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian sebuah bahasa. Saat ini, bahasa daerah seakan berperang dan beradu dengan berkembangnya zaman dan majunya peradaban. Fenomena ini tidak hanya menggerogoti wilayah-wilayah perkotaan, tetapi juga wilayah-wilayah pedesaan yang akses transportasinya terbatas dan jauh dari ibu kota kabupaten. Hal ini dapat dilihat dengan tanda-tanda yang ditunjukkan dari terjadinya pergeseran dan peralihan penggunaan bahasa daerah ke bahasa yang lebih dominan, misalnya lingua franca di wilayah tersebut. Akibatnya, bahasa daerah kian terasa asing di tanahnya sendiri.

Bahkan, posisi bahasa daerah menjadi setara dengan bahasa asing. Bahasa daerah bukan bahasa pertama, bukan bahasa ibu. Pergeseran ini secara cermat diamati oleh Gufron A. Ibrahim, seorang guru besar di bidang antropolinguistik dari Maluku Utara, pada 9 Oktober lalu dalam Kuliah Umum Kebahasaan bertajuk “Tantangan dan Upaya Pelestarian Bahasa Daerah yang Terancam Punah di Indonesia”. Dalam penyampaiannya, Ibrahim menyampaikan bahwa kondisi pewarisan dan peralihan bahasa daerah dikelompokkan dalam tiga generasi yang memiliki kriteria berbeda-beda. Pertama, generasi >75 merupakan generasi yang cakap bahasa etnik dan setia menggunakannya. Kedua, generasi >50 merupakan generasi yang cakap bahasa etnik dan cakap bahasa lingua franca, tetapi lebih membiasakan generasi berikut dengan bahasa lingua franca. Ketiga, generasi <25-an merupakan generasi yang hanya cakap bahasa lingua franca sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Realitas ini menunjukkan makin menurunnya fungsi dan peran bahasa daerah di masyarakat, termasuk di Provinsi Maluku.
Upaya konkret untuk mengantisipasi terjadinya kepunahan dan penurunan daya hidup bahasa tersebut adalah revitalisasi. Menurut Hinton, Huss, dan Roche (2018) dalam The Routledge Handbook of Language Revitalization, revitalisasi bahasa merupakan segala upaya yang disengaja untuk membalikkan penurunan fungsi atau jumlah penutur suatu bahasa dengan tujuan mengembalikan vitalitasnya, baik dalam komunitas penutur asli maupun generasi baru. Revitalisasi bukan sekadar tindakan linguistik, melainkan sebuah gerakan sosial, budaya, dan politik yang melibatkan masyarakat penutur, lembaga pendidikan, serta pemerintah dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah. Program ini umumnya diaktualisasikan melalui pendekatan pendidikan dan pelibatan komunitas tutur. Dalam ranah pendidikan, sekolah menjadi salah satu ruang vital. Melalui pembelajaran yang terstruktur diharapkan dapat menciptakan penutur baru pelestari bahasa daerah. Dalam tulisan ilmiah berjudul “Education and Regional Languages in Indonesia: Between Necessity, Indifference and Regret” oleh Jerome Samuel (2025) berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan pendidikan bahasa daerah di sekolah menjadi elemen penting dalam menjaga bahasa daerah agar tidak makin terpinggirkan. Pandangan ini selaras dengan pendapat Shah, Sheena & Brenzinger, Matthias (2018) dalam “The Role of Teaching in Language Revival and Revitalization Movements. Annual Review of Applied Linguistics” bahwa pengajaran formal termasuk melalui sekolah merupakan cara utama atau satu‐satunya untuk meneruskan bahasa leluhur ketika transmisi antargenerasi sudah terganggu.
Sayangnya, pembelajaran bahasa daerah di wilayah multibahasa menghadirkan sebuah dinamika yang kompleks dan bukanlah menjadi perkara mudah. Di wilayah multibahasa dan multibudaya dengan tingkat diversitas yang tinggi, seperti Maluku, pendekatan ini menemukan banyak tantangan dan kendala. Dalam satu wilayah, siswa, dan pengajar bisa saja memiliki bahasa ibu yang berbeda. Tak hanya antara pengajar dan siswanya, di antara sesama siswa pun memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda yang tentunya akan memengaruhi efektivitas pembelajaran. Misalnya, di wilayah bagian selatan Pulau Seram, Jazirah Leihitu, pesisir Pulau Buru, dan Kota Dobo. Di wilayah-wilayah ini, dalam satu kelas dan dalam satu sekolah terdapat banyak kelompok suku, misalnya ada orang Jawa, Buton, Bugis, dan Makassar serta beberapa kelompok masyarakat lainnya di Maluku. Hal ini tentu menjadi sebuah kendala karena pembelajaran bahasa daerah tidak sekadar penguasaan kosakata dan tata bahasa, tetapi juga tentang pemahaman identitas dan nilai-nilai budaya luhur yang menyertainya dan orang akan cenderung ingin mempelajari bahasa daerahnya sendiri.
Tak hanya itu, pengajaran dan pembelajaran dalam upaya revitalisasi ini dihadapkan pada tantangan multidimensional. Di beberapa wilayah dan/atau sekolah dengan iklim bahasa dan budaya yang cukup homogen, seperti di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru ditemukan kendala dan tantangan yang berbeda. Menurunnya jumlah penutur bahasa daerah membawa dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Banyak pengajar atau guru saat ini bukan lagi penutur aktif bahasa yang mereka ajarkan. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran kehilangan keautentikan linguistik dan kultural yang seharusnya melekat dalam pengajaran bahasa daerah. Padahal, penguasaan terhadap bahasa yang diajarkan merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kondisi dan situasi ini menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya memerlukan kebijakan kurikulum, tetapi juga penguatan kapasitas guru sebagai penutur bahasa itu sendiri. Kendala ini makin diperparah dengan belum tersedianya jurusan atau program studi bahasa daerah di perguruan tinggi di Maluku. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya lembaga formal yang secara khusus menyiapkan tenaga pendidik profesional di bidang bahasa daerah.
Berbagai realita dan fenomena ini menunjukkan bahwa revitalisasi bahasa daerah di wilayah multibahasa memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adnyana Ida Bagus, dkk. (2025) dan dipublikasi dalam “Mother Tongue Matters: A Critical Study of Indigenous Language Integration in Formal Education Systems” dinyatakan bahwa dalam kebijakan dan praktik pendidikan, bahasa daerah tidak hanya sebagai media pengajaran, tetapi juga sebagai elemen penting pelestarian dan pemberdayaan budaya yang membutuhkan integrasi yang efektif sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah, pendidik, dan komunitas adat. Dalam konteks tersebut, keberhasilan revitalisasi bahasa daerah di wilayah multibahasa sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan pendidikan dan pemberdayaan komunitas tutur. Keterlibatan komunitas penutur asli juga menjadi unsur penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang alamiah. Hal ini diperkuat dengan temuan Komalasari (2024) dalam tulisan ilmiahnya berjudul “Strategies for Revitalizing the Banjar Language in Banjarmasin City” yang diterbitkan dalam International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding bahwa upaya revitalisasi bahasa Banjar berhasil ketika ada pelibatan beberapa komponen yang komprehensif, di antaranya komunitas, kebijakan sekolah, kurikulum lokal, serta dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajaran bahasa di sekolah perlu didukung dengan ketersediaan kelompok tutur yang juga aktif berbahasa daerah. Revitalisasi yang diupayakan pada ranah pendidikan tidak dapat mencapai hasil maksimal jika bahasa daerah tidak hidup dan tumbuh dalam rumah dan keluarga. Revitalisasi bahasa daerah bukan sekadar persoalan kurikulum, melainkan gerakan sosial yang menuntut keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar bahasa daerah benar-benar kembali hidup di tengah komunitasnya.